Tren penerbitan mandiri (self/independent publishing) sudah tak terbendung lagi. Kini, semakin banyak saja individu atau lembaga dari berbagai strata sosial dan ekonomi memanfaatkannya. Keberadan mereka, di satu sisi sungguh-sungguh semakin menggairahkan dinamika penerbitan nasional. Namun di sisi lain, menjamurnya penerbitan mandiri juga berarti “tercuri”-nya sebagian dari ceruk atau potensi pasar penerbitan-penerbitan umum. Walau begitu, sejauh tren tersebut semakin memperkaya khasanah perbukuan nasional, rasanya patut disambut positif.
Mengapa self/independent publishing menggejala bahkan bisa dikatakan semakin ngetren? Barangkali, itu merupakan pendobrakan atas dominasi cara penerbitan sebelumnya yang masih didominasi oleh penerbitan-penerbitan umum. Begitu kran demokrasi dibuka lebar-lebar, soal penerbitan pun bukan sesuatu yang sakral lagi dan sekarang semua orang bisa melakukannya.
Pada prinsipnya, keuntungan terbesar yang bisa diraih manakala kita menjadi self-publisher adalah pada kebebasan untuk menentukan apa pun bentuk, rupa, dan isi buku yang kita terbitkan nantinya. Namun demikian, ruang bebas itulah yang sejatinya bisa kita tarik-ulur untuk mendapatkan berbagai potensi dan manfaat lainnya. Saya coba ulas secara singkat di bawah ini.
1. Penampung tema-tema buku di luar mainstream penerbitan. Bukan rahasia lagi, salah satu alasan self-publishing adalah kesulitan penulis untuk mendapatkan penerbit yang mau menerbitkan naskahnya. Terlebih bila naskah tersebut tidak memenuhi standar kualitas atau tidak segaris dengan kepentingan, visi, dan misi penerbit. Terkadang, naskah-naskah yang membahas tema sangat spesifik, naskah peka dan bertendensi kontroversi, naskah sangat unik, naskah pembelaan (buku putih), atau naskah propaganda, kurang diminati penerbit umum.
Di sinilah alternatif self-publishing menjadi solusi. Kalau kita menjadi self-publihser, kita bisa menerbitkan naskah jenis apa pun sepanjang itu memenuhi kepentingan dan kebutuhan kita. Soal kualitas isi, format, kemasan, redaksional, dan hal teknis lainnya, kita sendirilah yang menetapkan. Bagi kalangan tertentu, sifat merdeka self-publishing tersebut begitu dinikmati dan dirasa mendatangkan kemanfaatan yang tak terbandingkan.
2. Manfaat branding institusi atau personal. Sudah tidak terbantahkan lagi, selain menjadi medium penyampai ide, pesan, dan gagasan, buku juga bisa dikemas sebagai communications tools. Bahkan belakangan, buku menjadi bagian atau pilihan dari strategi branding (penciptaan dan pengembangan merek diri). Buku adalah tenaga “humas” atau pemoles citra yang efektif, dan semakin sering menjadi pilihan alat untuk menggapai brand awareness pribadi maupun lembaga.
Nah, bila kita menjadi self-publihser, kita punya kuasa sepenuhnya untuk memanfaatkan potensi buku sebagai brand creator atau bahkan brand domination. Lihat bagaimana Hermawan Kartajaya yang biasa menggunakan penerbitan besar dan mapan, akhirnya toh membuat penerbitan mandiri demi semakin memoles brand MarkPlus&Co. Simak pula bagaimana Andrie Wongso mengukuhkan dominasi kiprah kemotivatorannya dengan penerbitan mandiri AW Publishing.
Ke depan, saya semakin yakin bahwa akan semakin banyak tokoh, lembaga, pribadi, atau kaum profesional yang memanfaatkan self-publishing sebagai leverage factor bagi kiprah publik atau karier mereka. Sebab, selain relatif lebih murah pembuatannya ketimbang pasang iklan di media massa cetak atau televisi, buku juga masih jauh lebih dihargai sebagai karya intelektual yang serius.
3. Manfaat iklan internal dan potensi iklan eksternal. Salah satu potensi yang belum banyak disadari atau dimanfaatkan oleh para self-publisher adalah potensi iklan dalam buku. Memang, pemanfaatan sebagian halaman buku bagi iklan internal (produk-produk sendiri) sudah umum sifatnya. Kebanyakan, iklan internal berisi judul-judul buku lain yang diterbitkan, iklan pelatihan, company profile, atau produk-produk penerbit mandiri lainnya yang masih relevan dengan judul buku.
Tetapi, potensi buku tema-tema tertentu dalam menggaet iklan atau sponshorship pihak luar tampaknya belum termanfaatkan secara maksimal. Padahal, buku-buku hobi, panduan, atau product knowledge selalu bersinggungan dengan produk-produk massal yang relevan. Ini berarti potensi iklan dan sudah selayaknya dimaksimalkan.
4. Potensi penjualan langsung. Salah satu alasan menarik mengapa sekarang begitu banyak profesional, lembaga konsultan, biro pelatihan, trainer, pembicara publik, pengajar, termasuk rohaniawan/pendakwah membentuk self-publishing adalah potensi penjualan buku secara langsung. Biasanya, kalau mereka menerbitkan buku di penerbitan umum, mereka hanya mendapatkan royalti sekitar 10 persen atau rabat pembelian langsung ke penerbit maksimal 30 persen (sebagian penerbit berani memberi diskon hingga 45 persen untuk pembelian tunai dalam jumlah besar).
Situasi akan berbeda hampir 180 derajat kalau mereka membuat penerbitan dan menerbitkan sendiri karyanya. Mereka bisa mendapatkan keuntungan maksimal atau nyaris bulat jika menerbitkan dan menjualnya sendiri. Seorang trainer, motivator, pembicara publik, atau pendakwah yang memiliki audiens/captive market yang jelas yang pasti jauh lebih mudah menjual sendiri bukunya. Saya menyaksikan, seorang pembicara publik bisa menjual buku sendiri 300-400 eksemplar sekali seminar selama dua jam. Bandingkan dengan rata-rata jumlah penjualan di toko buku dalam situasi normal. Jauh sekali, bukan?
5. Potensi bisnis penerbitan. Sebuah buku terbitan sendiri yang sukses atau laku keras jelas membuka peluang penerbitan buku-buku berikutnya. Dalam hitung-hitungan sederhana, sebuah judul buku yang laris (sekali cetak) hasilnya bisa digunakan untuk sekali cetak ulang dan cetak satu judul baru. Kalau lebih efisien lagi production cost-nya, perbandingannya bisa satu buku sukses kemudian menghasilkan sekali cetak ulang judul lama dan cetak lagi satu setengah judul baru. Rasio inilah yang bila dikelola dengan baik bisa mentransformasi self-publishing menjadi bisnis penerbitan berskala besar.
Nah, silakan menyimak kasus berikut ini. Untuk satu judul buku saja, ESQ, karya Ari Ginanjar yang diterbitkan sendiri itu bisa sampai tercetak 500.000 eksemplar lebih. Taruh saja asumsi sekali cetak sekitar 5.000 eksemplar (faktanya pasti lebih), berarti buku itu sudah 100 kali cetak. Masih dengan rasio sekali cetak untuk satu judul menghasilkan sekali cetak ulang dan sekali cetak satu judul baru, maka hitungan terkasar menunjukkan minimal ada 200 judul baru bisa diproduksi. Ingat, itu baru dari satu judul buku yang sukses fenomenal (mega-bestseller) dan meng-generate potensi penerbitan judul-judul baru lainnya.
Dari hitung kasar saya dan dengan harga konstan buku Rp45.000 (2001-2007), satu judul ESQ (baik diterbitkan sendiri atau misalnya diterbitkan penerbit lain) tadi sudah memberikan pendapatan royalti kepada penulisnya sebesar Rp2,125 miliar. Apabila self-publishing Ary Ginanjar menggunakan distributor berdiskon 50 persen, pendapatan yang diraih sebesar Rp10,625 miliar atau net profit Rp4,250 miliar (nyaris Rp50 juta per bulan).
Apabila separuh saja dari oplah 500.000 eksemplar itu dijual secara direct selling melalui pelatihan-pelatihan, maka pendapatan yang diraih mendekati Rp16 miliar. Atau, jika seluruh oplah buku tersebut dijual melalui direct selling, maka hasil yang dinikmati oleh penerbitan sendiri ini mencapai Rp21,250 miliar. Makanya, siapa bilang jadi penulis dan penerbit mandiri nggak bisa jadi miliarder he he he…?![ez]
* Edy Zaqeus adalah seorang editor profesional, konsultan, self-publisher, dan penulis buku laris Resep Cespleng Menulis Buku Bestseller (Fivestar, 2008). Ia dapat dihubungi melalui email: edzaqeus@gmail.com atau melalui website: www.pembelajar.com dan weblog: http://ezonwriting.wordpress.com. Catatan: Artikel ini telah dimuat sebelumnya di Majalah MATABACA Volume 6, No.12, Agustus 2008 (Edisi Khusus Ulang Tahun).
Langganan:
Posting Komentar (Atom)






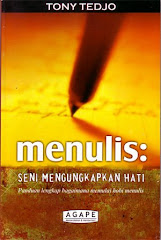




1 komentar:
Bahan pertimbangan
Posting Komentar